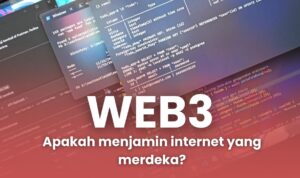http://gajayanatvnews.com – Inkompetensi adalah sinyal berbahaya. Apalagi bila melekat pada diri seorang pemimpin. Tanpa kemampuan yang mumpuni, pemimpin menjadi ibarat seorang nahkoda buta menavigasi kapal megah di tengah samudra yang bergelombang. Ia tak tahu arah angin, tak paham peta, tak bisa membaca bintang. Yang ia punya hanya keyakinan buta bahwa lautan akan bersikap ramah. Maka kapal itu pelan-pelan kehilangan arah, awaknya kebingungan, dan penumpangnya mulai saling mencurigai. Nahkoda ini bukan sekadar metafora, ia cerminan dari bagaimana negara ini dikelola ketika kompetensi bukan lagi syarat, dan pertimbangan rasional digantikan kepentingan politik sesaat.
Inkompetensi, dalam konteks ini, lebih terarah pada kekosongan pikiran yang memunculkan tindakan-tindakan gegabah, berakibat hilangnya pedoman moral, hilangnya titik tuju dan menyebabkan orang lain menjadi korban. Dalam etika Immanuel Kant, idealnya kompetensi pada manusia itu berdasarkan pada yang rasional dan bermoral. Ia tidak boleh dijadikan sekadar alat untuk tujuan lain, betapapun mulianya tujuan itu. Kant, seorang filsuf Jerman, meletakkan prinsip otonomi moral sebagai landasan: setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip yang bisa dijadikan hukum universal (categorical imperative). Dalam konteks negara, ini berarti kebijakan publik harus lahir dari rasionalitas murni yang mempertimbangkan martabat manusia, bukan dari kalkulasi politik yang mengorbankan rakyat sebagai alat.
Situasi Kebalikan
Namun hari ini, kita menyaksikan kebalikan dari itu. Kabinet Merah Putih bentukan Presiden menunjukkan kecenderungan yang merisaukan. Beberapa menteri dipilih bukan karena kapasitas dan kompetensinya, tetapi karena loyalitas politik atau kepentingan koalisi, dan wakil menteri rangkap jabatan, berambisi menjadi komisaris demi tingginya gaji. Ini bukan tuduhan kosong. Latar belakang beberapa menteri sangat jauh dari bidang yang mereka kelola. Ketika seorang menteri, misalnya, tak memiliki rekam jejak di bidang energi tetapi ditugaskan mengelola sektor strategis tersebut, maka kita sedang bermain-main dengan nasib jutaan warga negara.
Kebijakan yang lahir pun mencerminkan kekosongan epistemik. Ketika kebijakan tidak didasarkan pada riset, data, atau analisa mendalam, maka kebijakan itu kehilangan legitimasi rasional. Misalnya, kebijakan subsidi yang salah sasaran, makan bergizi yang (kerap kali) malnutrisi, kebijakan menyesatkan soal tanah, rekening, hingga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme hampir di semua lini institusi. Ada lagi, penundaan program-program esensial demi manuver politik jangka pendek. Ini bertentangan dengan prinsip Kantian bahwa tindakan moral harus bisa dijustifikasi secara rasional dan tidak semata-mata berdasarkan tujuan pragmatis.
Inkompetensi dalam Pendidikan
Inkompetensi itu kemudian menjalar ke institusi pendidikan, tempat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun akal budi bangsa. Baru-baru ini, Indeks Risiko Integritas Riset yang dikembangkan oleh Profesor Lokman Meho dari American University of Beirut, menunjukkan bahwa integritas riset di 13 perguruan tinggi di Indonesia berada dalam “zona merah”. Ini bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan sinyal bahwa etika dan nalar akademis bangsa sedang runtuh.
Pendidikan tinggi, yang seharusnya menjunjung sapere aude (beranilah berpikir sendiri), justru menjadi tempat pragmatisme akademik. Dosen didorong untuk memenuhi kuota publikasi tanpa pendalaman ilmiah. Plagiarisme dan fabrikasi data terselubung menjadi rahasia umum. Dana penelitian digunakan tanpa akuntabilitas ilmiah. Hal ini mengarah pada pelanggaran imperatif moral Kant, karena ketika pengetahuan direduksi menjadi alat birokratis belaka, maka martabat ilmu dan manusia yang memproduksinya ikut hancur.
Lebih parah lagi, krisis itu kini menjalar ke pendidikan dasar dan menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan kebijakan kurikulum baru, yang diklaim: “mendalam”, “revolusioner” namun tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa pelatihan yang serius kepada guru, dan tanpa riset longitudinal terhadap dampak kebijakan serupa di negara lain. Guru-guru kebingungan. Mereka dibebani jargon-jargon baru yang tidak membumi dan target-target evaluasi yang berubah-ubah. Anak-anak sebagai peserta didik pun menjadi korban eksperimen kebijakan yang tak berbasis pada evaluasi ilmiah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka (Permendikdasmen, No. 13 Tahun 2025). Kurikulum ini merancang fleksibilitas, pengatan kompetensi, dengan pendekatan pembelajaran mendalam bagi para peserta didik di seluruh Indonesia. Lalu, di Kementerian Agama memunculkan Kurikulum Berbasis Cinta, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6077 Tahun 2025. Lalu, di Kementerian Sosial, muncul lagi sekolah rakyat dengan kurikulum berbasis tiga tiga pilar: Kurikulum Karakter dan Asrama. Tiga kurikulum yang dipakai, yang diklaim untuk anak bangsa. Pertanyaan yang mengemuka, kurikulum mana yang digunakan Merdeka, Cinta, atau Karakter Berasrama?
Pertanyaan itu menimbulkan kebingungan masif. Pihak yayasan, kepala sekolah, guru-guru di daerah terpencil kemungkinan kurang paham bagaimana menyusun turunan praktis dan administrasi dari kurikulum yang relevan dan terukur, sementara sekolah di kota besar berlomba-lomba mengejar kuantitas, hasil, tanpa mempertimbangkan proses belajar. Dalam logika Kantian, ini adalah bentuk dehumanisasi sistemik memperlakukan anak-anak dan guru sebagai objek dari eksperimen kebijakan, bukan sebagai subjek rasional yang layak diajak berdialog.
Warga negara kompeten
Sebagai warga negara, saya meragukan pemimpin inkompeten. Beragam alibi dari pemimpin inkompenten saat terjadi kegagalan: “ini proses belajar”, “nanti dibenahi”, “yang penting hasil”, “demi normalisasi”, menjadi bentuk sikap dan tindakan oportunis. Menjadi pemimpin mestinya adalah seorang nahkoda yang paham tentang navigasi, visi-misi rasional, sistem yang mempertimbangkan kepastian dan kemudahan, merajut pikiran yang komprehensif. Pemimpin yang sibuk mem-mbois-kan diri, memajang gambar diri tanpa tahu diri, nir-prestasi, adalah situasi bahwa institusi mulai oleng, terjadi kebingungan, kecemasan, hingga muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab pada semua ini? Problem utama yang tidak disudahi, bermuara pada satu hal: inkompetensi. Ketidakmampuan mengelola negara, kota, dan pendidikan tinggi berarti berpotensi menghasilkan kerusakan.
Negara, oleh karena itu, dalam pandangan Kant, harus dibangun di atas prinsip moral publik, hukum yang bisa diterima oleh semua orang jika mereka berpikir secara rasional dan adil. Ketika institusi negara diisi oleh individu-individu yang tidak memiliki kompetensi, dan ketika kebijakan disusun tanpa akal budi dan prinsip moral, maka negara tersebut sedang berjalan menuju kerusakan struktural. Lebih penting lagi, inkompetensi bukan hanya kesalahan individu, ia adalah dosa institusional. Ia menyebar seperti penyakit. Ketika satu menteri tidak kompeten, ia tidak hanya gagal mengurus sektornya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem. Ini menciptakan efek domino: perguruan tinggi kehilangan arah, pendidikan dasar kacau, dan rakyat semakin sinis terhadap demokrasi.
Sebagai warga negara kompeten, kita tidak boleh diam. Kant mengajarkan bahwa manusia memiliki tugas moral untuk menegakkan prinsip rasional dalam kehidupan publik. Dalam bahasa kontemporer: kita harus menuntut akuntabilitas, menolak kebijakan yang tidak berbasis data, dan menolak penunjukan pejabat publik berdasarkan politik balas budi. Inkompetensi bukan sekadar kelemahan, ia adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat. Dan seperti kekerasan lainnya, ia harus dilawan dengan nalar dan kata. Maka, kita perlu berani berkata: cukup sudah, bila tidak mau terjerumus pada negara gagal.
(Andri Fransiskus Gultom, Akademisi dan Pendiri Institut Filsafat Pancasila)